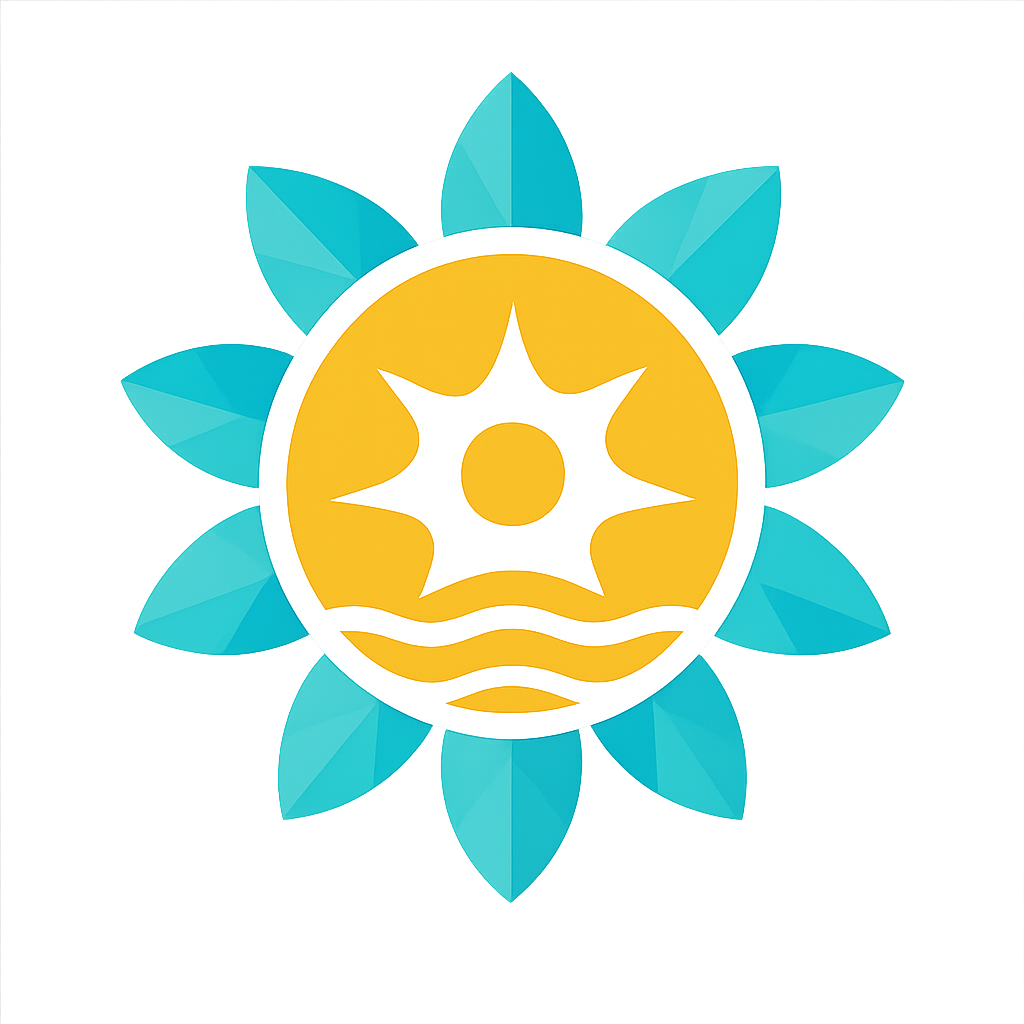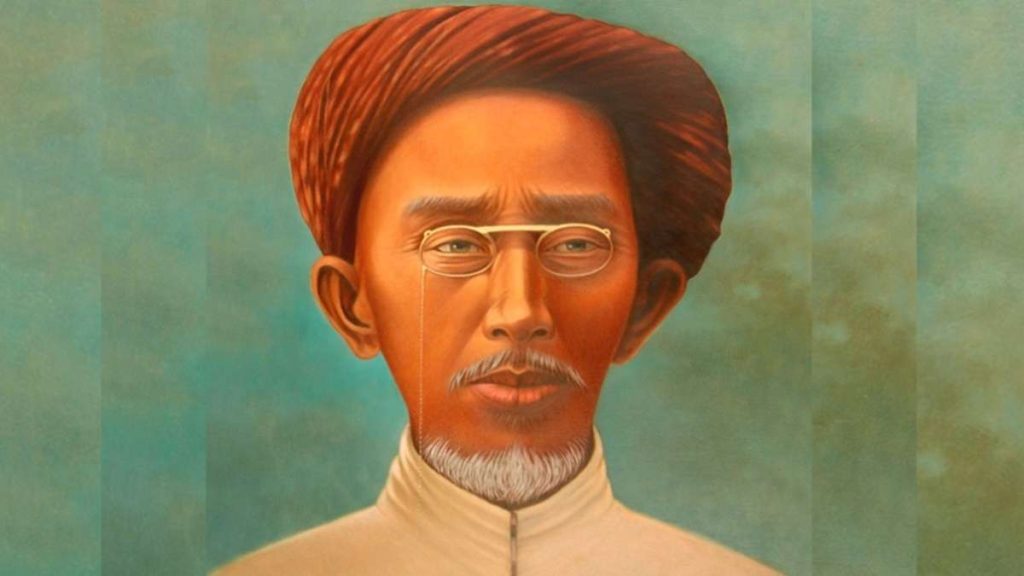credit sampul: x.com
Lucu sekali, kita ini hidup di negeri yang katanya demokratis. Katanya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi, rupanya Tuhan di sini hanya kerja sebagai tukang hitung. Ia menghitung suara satu per satu, lalu selesai. Tidak ada yang didengar, apalagi ditindaklanjuti.
Suara Itu Hanya Angka, Bukan Aspirasi
Cobalah bayangkan. Rakyat antre panjang, panas-panasan, memegang selembar kertas sakral, lalu memasukkannya ke kotak suara. Eh, ujung-ujungnya, kertas itu hanya jadi angka di Excel. Angka siapa yang terbanyak, itulah yang jadi raja. Aspirasi? Ah, itu bonus. Kalau ada, syukur. Kalau tidak, ya nasib.
Pasar Malam Demokrasi
Lebih konyol lagi, suara itu bisa dibeli. Ada yang datang bagi-bagi sembako, uang receh, atau janji proyek. Rakyat pun menjual haknya, karena lapar memang lebih nyata daripada demokrasi.
Dan ketika suara sudah dibeli, pembelinya tentu merasa punya hak istimewa:
- Merampok anggaran? Wajar.
- Nepotisme? Sudah harga paket.
- Rakyat protes? Ah, wong suaranya sudah dibeli kok. Diamlah, jangan cerewet.
Demokrasi? Lebih Mirip Lelang
Mari jujur saja: ini bukan pesta demokrasi. Ini lelang suara. Siapa yang punya modal lebih besar, dialah yang menang. Setelah menang, yang kalah tetap rakyat. Karena apa pun hasilnya, yang berkuasa tetap sibuk menghitung untung, bukan mendengar jeritan.
Komoditas Politik?
Pada akhirnya, kenapa suara rakyat tidak didengar? Karena dari awal memang tidak ada niat untuk mendengar. Yang ada hanyalah niat menghitung. Demokrasi di sini ibarat lomba cerdas cermat: siapa yang dapat angka tertinggi, dialah pemenangnya. Bedanya, pemenang tidak perlu pintar, cukup modal amplop tebal dan relasi penguasa. Pemilih hanyalah komoditas politik, dibutuhkan suaranya saja untuk menyumbang tally counter di papan. Sisanya? sudahlah…