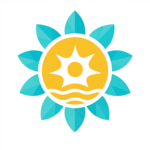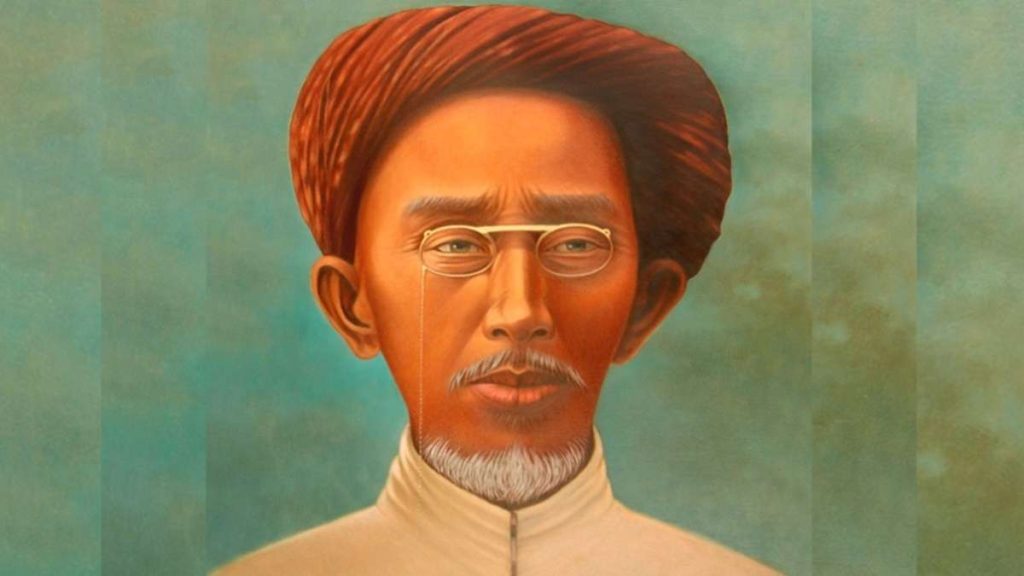Mentari.or.id-Pendidikan kita, sedang berdiri di persimpangan jalan yang gawat. Kita terjebak dalam sebuah “fetisisme angka” sebuah pemujaan berlebihan terhadap skor yang dianggap sebagai representasi tunggal dari kebenaran intelektual dan moral. Di sinilah, retorika kemajuan yang kita agungkan mulai terasa hambar jika hanya berakhir pada pengejaran statistik yang mekanistik.
Secara analitik, skor atau nilai adalah upaya reduksionistis. Ia mencoba memeras kompleksitas kognitif, gejolak emosi, dan kedalaman spiritual murid ke dalam sebuah besaran skalar. Dalam logika positivistik, apa yang tidak bisa diukur dianggap tidak ada. Maka, ketika seorang murid memiliki ketulusan hati (ikhlas) dalam membantu kawannya, namun gagal menghafal rumus kalkulus yang rumit, sistem pendidikan kita cenderung mencapnya sebagai “gagal”.
Ini adalah pengkhianatan ontologis. Kita sedang mengubah sekolah dari “taman” menjadi “pabrik”. Guru tidak lagi berperan sebagai petani yang menyemai benih karakter, melainkan sebagai mandor yang memastikan setiap produk memiliki spesifikasi angka yang seragam. Skor telah menjadi berhala baru. Kita takut pada angka 55 lebih daripada kita takut pada hilangnya kejujuran dalam jiwa anak didik kita.
Namun, apakah hari ini kita tidak sedang membangun kejumudan baru? Sebuah ortodoksi angka di mana kurikulum yang kaku memaksa guru untuk lebih mencintai tumpukan kertas ujian daripada mencintai binar mata muridnya yang sedang bertanya tentang hakikat Tuhan.
Dilema Guru: Antara Penjaga Ruh dan Juru Tulis Angka
Mari kita tengok wajah guru-guru kita. Di balik senyum mereka yang tegar, tersimpan keletihan yang eksistensial. Guru memikul beban ganda: sebagai pendidik ( muaddib ) dan sebagai pegawai administratif. Waktu mereka habis untuk mengisi aplikasi, mengejar target kurikulum, dan memastikan skor rata-rata kelas tidak anjlok di bawah Standar Ketuntasan Minimal.
Pena guru tak lagi menuliskan nasihat-nasihat emas di relung hati murid, melainkan sibuk menggoreskan tinta merah pada lembar jawaban yang salah. Guru telah direduksi menjadi “operator skor”. Hubungan antara guru dan murid yang seharusnya bersifat keintiman spiritual, bergeser menjadi perilaku yang dingin dan transaksional.
Padahal, ruh pendidikan yang sejati adalah transfer of values, bukan sekadar transfer of scores. Jika guru hanya mengejar skor, maka ia tak lebih dari sebuah mesin hitung yang bernapas. Ia kehilangan otoritas moralnya karena ia tak lagi melihat murid sebagai pribadi yang unik, melainkan sebagai variabel dalam rumus akreditasi sekolah.
Jebakan Teknokratisasi Pendidikan
Demi menarik minat orang tua, sekolah-sekolah kita memajang skor ujian nasional tertinggi atau jumlah lulusan yang masuk ke perguruan tinggi negeri di baliho-baliho besar di pinggir jalan.
Ini adalah bentuk teknokratisasi pendidikan yang mencemaskan. Kita seolah-olah mengamini bahwa mutu pendidikan hanya ditentukan oleh output yang bisa dikuantifikasi. Apakah keluasan hati itu bisa diukur dengan skor 0 sampai 100?
Kita perlu melakukan otopsi terhadap kebijakan evaluasi kita. Skor seharusnya hanyalah “umpan balik”, sebuah kompas kecil untuk mengetahui di mana posisi kita, bukan “tujuan akhir”. Namun, dalam praktiknya, skor telah menjadi “hakim” yang menjatuhkan vonis mati atas rasa percaya diri seorang anak.
Menghayati Proses di Tengah Badai Hasil
Ada sebuah ironi yang tajam dalam dunia pendidikan kita: kita mengagungkan hasil, namun membenci proses. Padahal, dalam pandangan Islam, yang dinilai oleh Allah adalah ikhtiar (proses), bukan semata-mata hasil. Namun, di meja-meja guru dan di ruang-ruang kepala sekolah, hasil adalah segalanya.
Seorang murid yang menyontek dan mendapatkan skor 90 seringkali lebih diapresiasi daripada murid jujur yang mendapatkan skor 60. Inilah letak kebangkrutan moral pendidikan kita. Dengan mendewakan skor, secara tidak langsung kita sedang mengajarkan anak-anak kita untuk menjadi pragmatis dan menghalalkan segala cara. Kita sedang mencetak generasi “pintar secara teknis” namun “cacat secara etis”.
Di sinilah peran lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk melakukan tajdid di bidang evaluasi. Mengapa kita tidak mulai memperhitungkan “skor karakter”, “skor kepedulian sosial”, atau “skor ketekunan”? Mengapa kita tetap terpaku pada angka-angka kognitif yang seringkali hanya menguji daya ingat jangka pendek, bukan daya nalar yang mendalam?
Menuju Pedagogi Cahaya: Melampaui Angka
Jika kita ingin keluar dari labirin angka ini, kita harus berani merumuskan kembali apa itu “keberhasilan pendidikan”. Keberhasilan seorang murid Muhammadiyah tidak boleh diukur dari seberapa fasih ia mengerjakan soal pilihan ganda, melainkan dari seberapa besar manfaat yang ia berikan kepada umat dan bangsa (khairunnas anfa’uhum linnas).
Guru harus dikembalikan marwahnya sebagai “pembuka hijab kegelapan”. Mereka harus diberikan ruang untuk tidak hanya mengejar materi kurikulum, tetapi juga untuk berdialog, berdiskusi, dan menyelami kegelisahan intelektual muridnya. Penilaian harus bersifat holistik—sebuah potret menyeluruh tentang manusia, bukan sekadar potongan-potongan mozaik yang terpisah.
Lembaga pendidikan Muhammadiyah harus menjadi pelopor dalam mendobrak standarisasi yang membunuh kreativitas. Standarisasi adalah musuh dari keunikan. Jika semua bunga di taman dipaksa untuk mekar di waktu yang sama dengan warna yang sama (skor yang sama), maka taman itu tak lagi indah, ia hanya sebuah perkebunan industri yang membosankan.
Akhirul Kalam: Mengembalikan Jiwa ke Dalam Kelas
Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Skor hanyalah alat, ia bukan segalanya. Ia adalah bayangan, bukan cahaya itu sendiri.
Bagi guru-guru Muhammadiyah, ingatlah bahwa di tangan kalian tidak hanya terletak raport murid, tetapi juga masa depan peradaban. Jangan biarkan pena kalian menjadi dingin karena hanya mengejar angka-angka mati. Hangatkanlah ia dengan kasih sayang, dengan doa di sepertiga malam, dan dengan semangat untuk melahirkan generasi yang tidak hanya “cerdas angka”, tetapi juga “cerdas makna”.
Lembaga pendidikan Muhammadiyah harus berdiri tegak di hadapan arus zaman yang serba terukur ini. Kita harus berani mengatakan bahwa ada hal-hal yang jauh lebih berharga daripada skor ujian: integritas, empati, keberanian membela kebenaran, dan ketundukan kepada Sang Khalik.
Lonceng sekolah itu akan segera berdentang lagi esok pagi. Mari kita pastikan bahwa dentangnya bukan lagi pengumuman pelelangan jiwa, melainkan sebuah simfoni pencerahan yang membebaskan manusia dari belenggu angka-angka. Sebab pada akhirnya, di hadapan Tuhan, kita tidak akan ditanya berapa skor matematika kita, melainkan seberapa besar cinta dan cahaya yang telah kita bagikan di dunia yang fana ini.
Bojonegoro, 5 Januari 2026
Penulis: Ajun Pujang Anom (Anggota Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Bojonegoro)
![]()