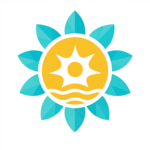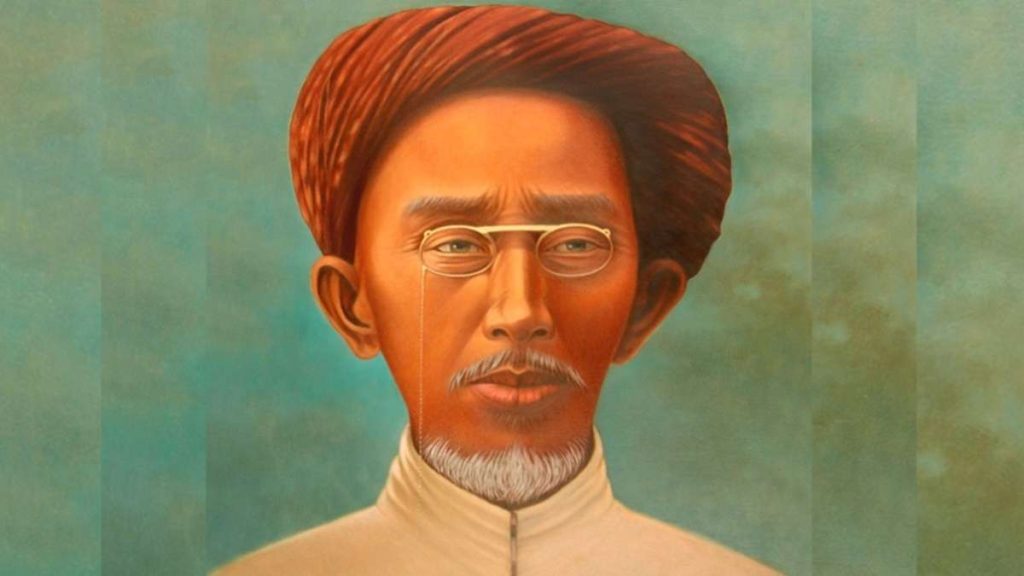Mentari.or.id, Sumberrejo – Di tengah gencarnya pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk berbagai program strategis nasional, muncul satu ironi yang sulit diabaikan: ketimpangan kesejahteraan antara guru honorer dan staf SPPG yang baru berjalan sekitar satu tahun namun telah diangkat sebagai PPPK. Fenomena ini bukan sekadar soal perbedaan status kepegawaian, melainkan potret nyata tentang arah prioritas kebijakan negara dalam memandang masa depan bangsa.

Gambar oleh instagram/@adian__napitupulu, melalui instagram
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, merupakan program ambisius yang menelan anggaran negara sangat besar. Secara tujuan, program ini patut diapresiasi karena menyasar pemenuhan gizi peserta didik. Namun, persoalan muncul ketika perhatian terhadap program kesejahteraan guru, terutama guru honorer justru tertinggal jauh. Padahal, gizi yang baik tanpa pendidikan yang bermutu hanya akan melahirkan generasi yang sehat secara fisik, tetapi rapuh secara intelektual dan karakter.
Lebih menyayat lagi, ketika staf SPPG yang notabene merupakan bagian dari program baru, dalam kurun waktu relatif singkat telah mendapatkan status PPPK dengan gaji dan jaminan kesejahteraan yang layak. Sementara itu, guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun, mengajar di ruang kelas sederhana, mendidik dengan dedikasi tinggi, dan menjadi fondasi utama kecerdasan bangsa masih harus bertahan dengan penghasilan yang jauh dari kata sejahtera. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana letak keadilan kebijakan negara?
Guru honorer bukan sekedar tenaga pelengkap sistem pendidikan. Mereka adalah aktor utama yang menjaga denyut nadi sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Namun realitasnya, pengabdian panjang tidak selalu berbanding lurus dengan pengakuan dan kesejahteraan. Puluhan tahun mengajar, puluhan tahun pula mereka menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Di sisi lain, staf SPPG yang baru seumur jagung justru “dimuliakan” oleh sistem.
Kondisi ini tentu menjadi bahan renungan serius bagi pemerintah. Jika salah satu program utama presiden adalah mempersiapkan generasi masa depan yang unggul, maka investasi terbesar seharusnya diarahkan pada kualitas dan kesejahteraan pendidik. Kecerdasan siswa adalah senjata utama bangsa dalam menghadapi persaingan global, dan senjata itu ditempa oleh guru bukan oleh program instan.
Ketimpangan ini juga mengungkap fakta pahit bahwa arah kebijakan sering kali ditentukan oleh kekuatan garis tangan penguasa, bukan oleh skala prioritas kebutuhan yang paling mendasar. Keputusan politik lebih cepat mengalir kepada program yang memiliki daya tarik simbolik dan citra, ketimbang kepada sektor yang bekerja sunyi namun berdampak jangka panjang seperti pendidikan.
Sudah saatnya pemerintah berhenti memandang kesejahteraan guru sebagai isu sampingan. Guru honorer tidak membutuhkan janji baru, melainkan keberpihakan nyata. Jika negara mampu mengangkat ribuan staf baru menjadi PPPK dalam waktu singkat, UM maka seharusnya negara juga mampu menyelesaikan persoalan ratusan juta guru honorer yang telah lama berkorban tanpa kepastian.
Pada akhirnya, masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dihabiskan, melainkan oleh seberapa tepat kebijakan itu menyentuh akar persoalan. Jika guru terus dikesampingkan, maka jangan heran jika cita-cita besar tentang Indonesia maju hanya akan menjadi slogan, tanpa fondasi yang kokoh.
![]()