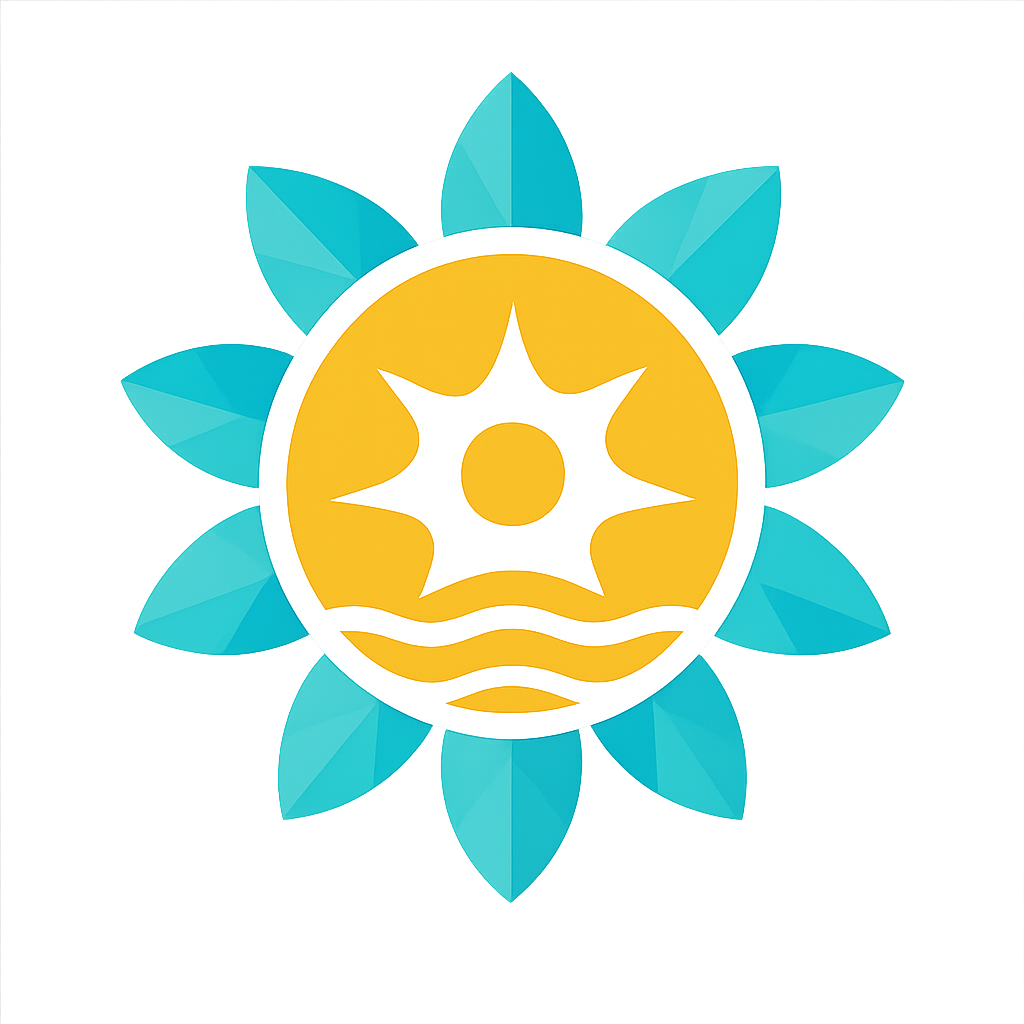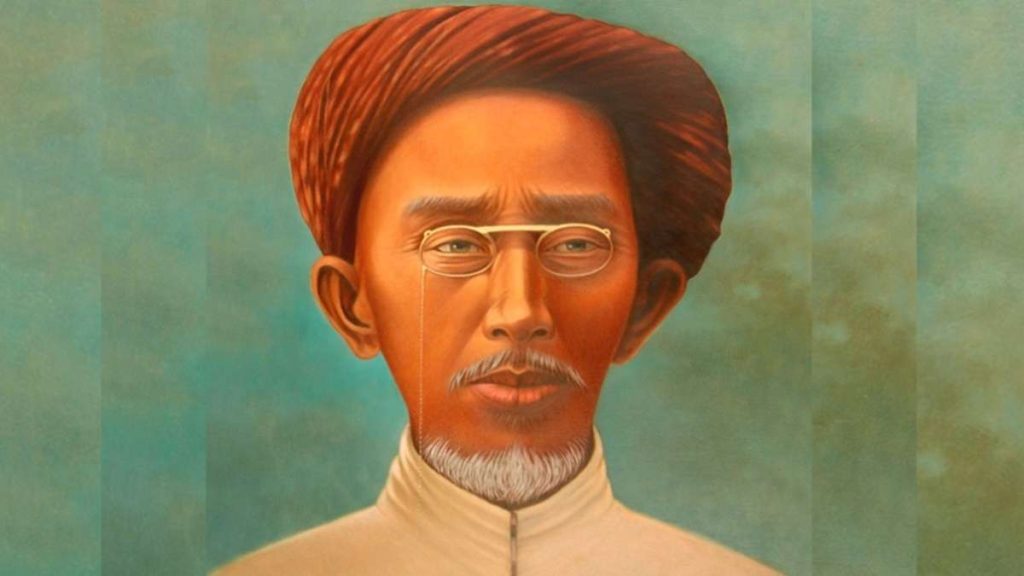Mentari.or.id-Di awal tahun 2026 ini, udara pendidikan kita tiba-tiba dipenuhi oleh aroma kertas baru dan harapan yang mengalun dari meja birokrasi. Terbitnya Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman bukanlah sekadar titah administratif. Bagi kita, ia adalah sebuah “surat cinta” yang cemas, sebuah pengakuan jujur dari negara bahwa sekolah-sekolah kita sedang tidak baik-baik saja. Sekolah telah lama menjadi ruang yang “dingin”, tempat di mana perundungan bersembunyi di balik tawa koridor dan depresi menyamar di balik nilai-nilai yang sempurna.
Namun, mari kita bedah dengan pisau analitik yang lebih dingin: Apakah budaya bisa diproduksi melalui pasal-pasal? Bisakah “rasa aman” dipaksakan melalui surat keputusan?
Bagi kita, kebijakan ini adalah cermin sekaligus tantangan. Sebagai organisasi yang telah memahat wajah pendidikan Indonesia jauh sebelum negara ini memiliki kementerian, Muhammadiyah berdiri di posisi yang unik. Ia bukan sekadar pelaksana kebijakan, melainkan penjaga ruh pendidikan. Permendikdasmen ini harus dibaca bukan sebagai beban teknokratis, melainkan sebagai momentum untuk mengembalikan sekolah sebagai baitul hikmah.
Melampaui Sekadar Bebas dari Pukulan
Permendikdasmen tersebut menekankan tiga pilar utama: kesehatan mental, mitigasi perundungan, dan inklusivitas. Secara lahiriah, ini adalah nilai-nilai universal yang memikat. Namun, dalam kacamata epistemologis, “aman” bukan hanya berarti tidak ada darah yang mengalir atau tidak ada tulang yang patah. Aman adalah sebuah kondisi ontologis di mana jiwa seorang murid merasa “pulang” ketika masuk ke gerbang sekolah.
Kebijakan ini menuntut lembaga pendidikan menyediakan dukungan psikologis awal. Di sini, tantangan bagi Muhammadiyah muncul: Selama ini, kita mungkin terlalu fokus pada kecerdasan kognitif dan ketangkasan berorganisasi (melalui IPM atau HW), namun seringkali abai pada kerapuhan interior murid. Kita sering menganggap kesedihan sebagai kurangnya iman, dan kecemasan sebagai tanda lemahnya tawakal.
Padahal, kesehatan mental adalah bagian dari menjaga nafs yang diperintahkan oleh agama. Muhammadiyah harus mampu menerjemahkan kebijakan ini menjadi sebuah “Teologi Perlindungan“. Sekolah di lingkup Muhammadiyah harus menjadi tempat di mana seorang murid yang sedang terluka batinnya tidak merasa dihakimi, melainkan dirangkul dengan tangan yang penuh kasih sayang.
Menghancurkan Arsitektur Keangkuhan
Perundungan bukanlah sebuah insiden yang berdiri sendiri; ia adalah anak kandung dari sebuah arsitektur keangkuhan. Ketika sekolah hanya menghargai mereka yang juara kelas atau mereka yang jago di lapangan, secara tidak langsung kita sedang menciptakan kasta. Dan di mana ada kasta, di sana ada penindasan.
Permendikdasmen itu menuntut tindakan kuratif dan preventif yang tegas. Namun, bagi lembaga pendidikan Muhammadiyah, mitigasi ini tidak boleh hanya berhenti pada sanksi administratif. Kita harus masuk ke ranah akhlak.
Jangan sampai kita sibuk memasang CCTV di setiap sudut sekolah untuk menangkap pelaku perundungan, namun kita lupa memasang muraqabah di dalam hati anak didik kita. Budaya sekolah yang aman di Muhammadiyah harus dibangun di atas fondasi egalitarianisme Islam. Di hadapan Tuhan, semua murid sama. Maka, di hadapan guru, tidak boleh ada murid yang merasa lebih berhak menindas hanya karena ia merasa lebih senior atau lebih kuat.
Menguji Kedalaman Aksi
Salah satu poin paling tajam dari kebijakan baru ini adalah tuntutan akan inklusivitas. Sekolah harus ramah bagi mereka yang “berbeda”—baik secara fisik, mental, maupun latar belakang sosial.
Ini adalah ujian bagi Muhammadiyah. Apakah secara praktik, sekolah-sekolah kita sudah benar-benar terbuka bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus? Apakah kita sudah menyediakan ruang bagi mereka yang memiliki kecepatan belajar yang berbeda?
Kebijakan Budaya Sekolah ini memaksa kita untuk meruntuhkan tembok-tembok eksklusivitas. Muhammadiyah harus membuktikan bahwa “Pendidikan Berkemajuan” adalah pendidikan yang tidak meninggalkan siapapun di belakang. Inklusivitas bukan sekadar menyediakan ram di tangga sekolah bagi kursi roda, melainkan menyediakan tempat di dalam hati kita bagi setiap keunikan manusia.
Jangan Menjadi Berhala Baru
Melihat adanya risiko besar dalam implementasi Permendikdasmen tersebut: Birokratisasi Rasa Nyaman. Ada ketakutan bahwa sekolah-sekolah di Muhammadiyah akan terjebak dalam perlombaan mengisi aplikasi, mengunggah dokumen mitigasi, dan menyusun laporan formalitas hanya demi dianggap “patuh” oleh kementerian.
Budaya sekolah tidak tumbuh dari tumpukan kertas laporan. Budaya sekolah tumbuh dari cara seorang guru menyapa muridnya di pagi hari. Budaya sekolah tumbuh dari bagaimana konflik diselesaikan di ruang kepala sekolah dengan semangat ishlah.
Lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak boleh membiarkan kebijakan ini menjadi “berhala” administratif baru. Kita harus melampaui standar kementerian. Jika kementerian meminta “Aman”, Muhammadiyah harus memberikan “Tentram”. Jika kementerian meminta “Nyaman”, Muhammadiyah harus memberikan “Berkah”.
Peran Strategis Guru Muhammadiyah sebagai Muaddib
Dalam narasi kebijakan ini, guru diposisikan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi kekerasan fisik maupun psikis. Namun, beban ini akan terasa sangat berat jika guru masih dipandang sebagai buruh kurikulum.
Di sinilah Muhammadiyah harus melakukan reposisi. Guru Muhammadiyah adalah seorang Muaddib—penanam adab. Adab tidak mungkin tumbuh di lingkungan yang penuh ketakutan. Oleh karena itu, sebelum sekolah bisa menjadi aman bagi murid, sekolah harus menjadi aman bagi gurunya terlebih dahulu. Guru yang sejahtera secara mental dan finansial akan memiliki energi yang cukup untuk memeluk keresahan murid-muridnya.
Kebijakan Budaya Sekolah tahun 2026 ini harus diawali dengan memanusiakan guru. Jangan sampai kita menuntut guru menjadi pahlawan anti-perundungan, sementara guru itu sendiri mengalami “perundungan sistemik” dari beban administratif yang tak masuk akal.
Akhirul Kalam: Menjemput Fajar Sekolah yang Beradab
Permendikdasmen ini adalah sebuah momentum, sebuah kairos dalam sejarah pendidikan kita. Ia adalah undangan bagi kita semua untuk berhenti sejenak dari kegilaan mengejar skor akademik dan mulai memperhatikan detak jantung kemanusiaan di ruang kelas.
Bagi Muhammadiyah, kebijakan ini adalah panggilan untuk kembali ke khittah. Sekolah Muhammadiyah harus menjadi prototipe dari masyarakat Islam yang sebenar-benarnya: aman, nyaman, inklusif, dan penuh kasih sayang. Kita tidak butuh sekolah yang tampak hebat di baliho tapi keropos di dalam jiwa. Kita butuh sekolah yang mampu melahirkan manusia-manusia tangguh yang tahu cara menghargai sesama manusia.
Mari kita jadikan kebijakan ini sebagai sarana perenungan di tengah badai zaman. Sebuah tool untuk berpikir dan kemudian bangkit untuk membangun budaya sekolah yang tidak hanya “lulus sensor” kementerian, tetapi juga “lulus sensor” kebajikan. Di bawah sinar surya, tidak boleh ada satu pun murid yang merasa ketakutan untuk bermimpi.
Bojonegoro, 18 Januari 2026
Penulis: Ajun Pujang Anom (Anggota Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Bojonegoro)