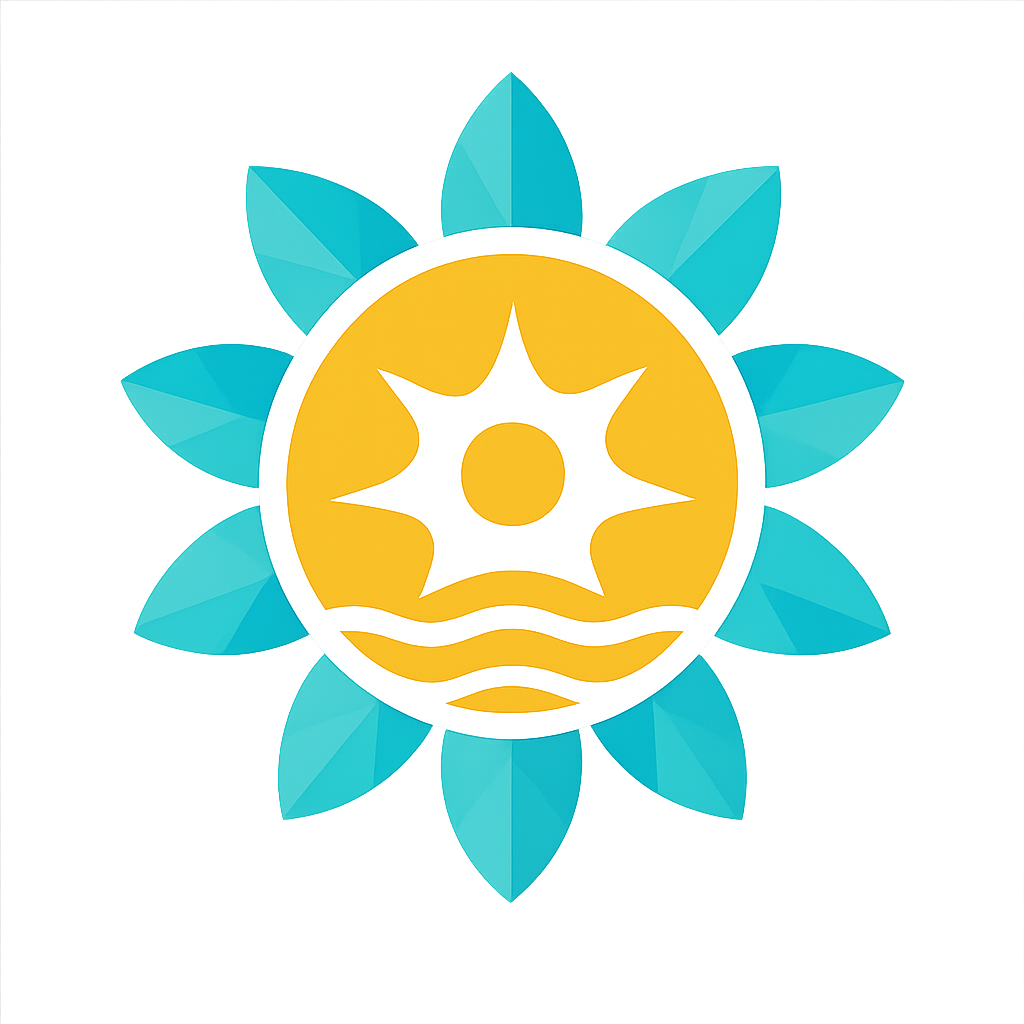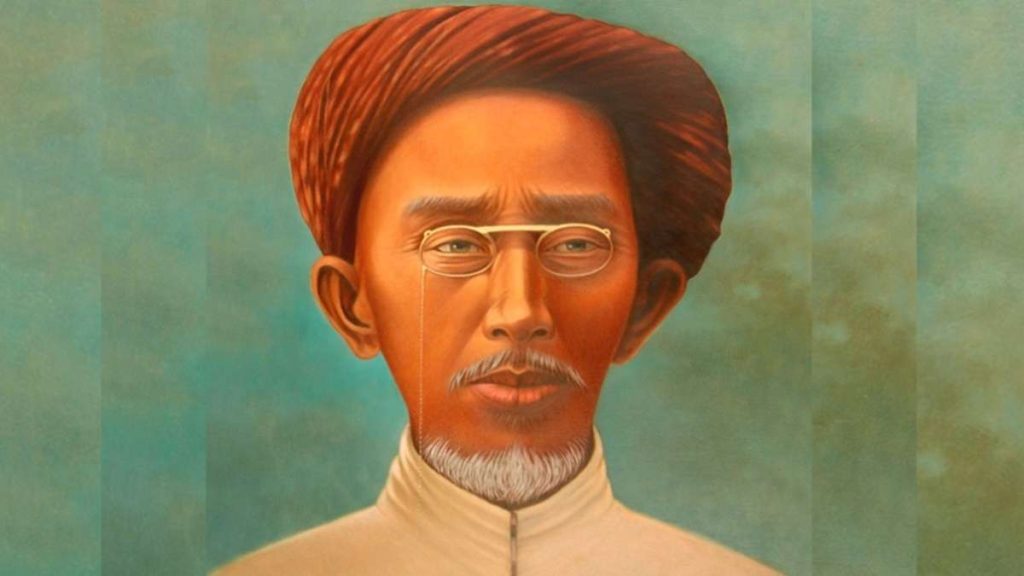Artikel otokritik oleh PenaFarhan.com
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.”
— Q.S. Ar-Ra’d: 11
Pernah menjadi pusat gravitasi ilmu pengetahuan, dunia Islam kini menghadapi kenyataan pahit: tertinggal dalam sains, teknologi, dan ekonomi global. Banyak analis menyalahkan agama, budaya, atau hukum Islam sebagai penyebab. Namun benarkah akar persoalannya di situ? Saya akan mencoba menjernihkan kebingungan itu dengan pendekatan historis, epistemologis, dan institusional — sambil mengkritisi narasi populer yang sering bias atau tidak utuh.
1. Dari Puncak Keemasan ke Era Kemandekan Intelektual
Pada masa keemasan, Islam memimpin dunia ilmu: Al-Khwarizmi meletakkan dasar aljabar, Ibnu Sina merumuskan ensiklopedia kedokteran, dan Ibnu Rusyd menjadi jembatan rasionalitas antara Islam dan Barat. Namun pada abad ke-11 ke atas, terutama setelah perpecahan politik dan tekanan dari luar seperti Mongol dan Perang Salib, lembaga-lembaga keilmuan melemah dan mulai terjadi dominasi pandangan keagamaan yang konservatif.
Ahmet T. Kuru dalam Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment menjelaskan bahwa aliansi antara negara dan ulama menjadikan intelektual independen tersingkir. Namun, ia tidak menyalahkan agama sebagai ajaran, melainkan struktur sosial-politik yang membatasi kebebasan berpikir.
“The real issue is not Islam as a belief system, but the institutional alliance that marginalizes independent scholars and traders.”
— Ahmet T. Kuru
2. Ketika Hukum Dibekukan dan Dimatikan: Gagal Menerjemahkan Nilai ke Realitas
Islam adalah agama yang lengkap, termasuk dalam urusan sosial, ekonomi, dan ekologi. Al-Qur’an dan hadits penuh dengan prinsip pelestarian alam: manusia sebagai khalifah di bumi (Q.S. Al-Baqarah: 30), larangan berbuat kerusakan (fasad) (Q.S. Al-A’raf: 56), serta perintah menjaga keseimbangan alam (Q.S. Ar-Rahman: 7–9).
Namun kenyataannya, umat Muslim hari ini justru kerap menjadi pelaku kerusakan, bukan pelestarian. Di banyak negara dengan mayoritas Muslim:
- Sampah dibuang sembarangan, bahkan ke sungai dan laut.
- Tambang dibuka tanpa regulasi, merusak hutan dan sumber air.
- Udara kota-kota besar tercemar akibat ketidakpedulian pada emisi dan transportasi.
Semua ini terjadi bukan karena Islam kurang ajaran tentang lingkungan, tetapi karena ajaran itu tidak dipahami, tidak dijalankan, atau hanya dijadikan slogan.
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia…”
— Q.S. Ar-Rum: 41
Di sinilah kegagalan besar umat Islam modern: memisahkan ilmu agama dari realitas kehidupan. Syariah dipersempit hanya menjadi urusan ibadah ritual, sementara aspek sosial dan ekologis dibiarkan rusak.
Yang lebih ironis, banyak penguasa, perusahaan, bahkan tokoh agama terlibat dalam perusakan itu, atau diam seribu bahasa ketika alam dirusak atas nama “kemajuan ekonomi.” Tidak ada mekanisme penegakan hukum berbasis syariah yang benar-benar melindungi bumi dari kerakusan.
Para ulama seperti Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, hingga Imam Al-Ghazali telah menulis bahwa kekuasaan tanpa keadilan adalah kezaliman, dan pemimpin yang membiarkan kerusakan berarti telah gagal menjalankan amanah kekhalifahan.
Masalahnya bukan pada hukum Islam, tetapi pada ketidakmampuan umat, khususnya penguasa dan lembaga agama, untuk menerjemahkan nilai-nilai itu ke dalam kebijakan dan perilaku nyata. Dunia Muslim, yang secara teologis seharusnya peduli, justru tertinggal — karena agama tidak dijadikan pendorong kebijakan, tapi hanya kosmetik seremonial.
3. Kegagalan Sistem Pendidikan: Banyak Hafal, Minim Paham
Salah satu akar ketertinggalan umat Islam dalam peradaban modern terletak pada kegagalan sistem pendidikan — bukan dalam kuantitas lembaganya, tetapi dalam substansi, arah, dan kualitasnya. Banyak negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, memiliki ribuan pesantren, madrasah, hingga universitas Islam. Namun, itu belum berbanding lurus dengan kemajuan keilmuan, teknologi, maupun etika sosial umat.
Dalam konteks ini, ada beberapa problem nyata:
a. Kultus terhadap hafalan, bukan pemahaman
Sistem pendidikan Islam klasik sangat menjunjung tinggi penghafalan teks suci dan matan kitab. Itu adalah warisan penting, tetapi ketika hafalan menjadi tujuan utama tanpa pemahaman mendalam dan nalar kritis, maka ilmu berhenti pada permukaan.
Di banyak lembaga pendidikan Islam:
- Santri atau siswa didorong menghafal kitab atau ayat, tapi tak selalu diajak mendiskusikan maknanya.
- Diskursus keilmuan cenderung dogmatis; kritik dianggap ancaman, bukan metode belajar.
- Ilmu umum dan ilmu agama dipisahkan secara dikotomis, padahal dalam sejarah Islam, keduanya saling melengkapi (contoh: Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khwarizmi adalah pakar agama sekaligus sains).
b. Keterputusan dari realitas sosial
Ilmu sering diajarkan dalam ruang yang steril dari realitas. Pelajaran fikih misalnya, dibahas secara hukum, tapi tak dikaitkan dengan praktik ekonomi, relasi gender, atau keadilan lingkungan. Siswa tahu rukun jual beli, tapi tak tahu bagaimana menghadapi praktik riba di dunia modern.
Di Indonesia misalnya:
- Kurikulum madrasah masih belum sepenuhnya menyatu dengan dinamika industri dan teknologi.
- Banyak lulusan pendidikan Islam yang gagap ketika memasuki dunia profesional non-agama.
- Kegiatan riset yang dihasilkan oleh kampus Islam lebih sering bersifat teoretis daripada aplikatif.
c. Kesenjangan mutu guru dan ketimpangan kebijakan negara
Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di banyak wilayah mayoritas Muslim adalah kesenjangan mutu tenaga pendidik, yang sebagian besar bukan karena kurangnya semangat atau dedikasi guru, melainkan akibat kebijakan negara yang tidak berpihak pada pemberdayaan guru secara adil dan merata.
Di Indonesia, misalnya:
- Banyak guru honorer di madrasah dan sekolah Islam swasta menerima gaji jauh di bawah UMR, bahkan tak jarang hanya diberi honor Rp200.000–Rp500.000 per bulan.
- Proses sertifikasi guru cenderung birokratis, lambat, dan tidak merata.
- Banyak guru madrasah swasta tidak mendapat akses pelatihan profesional, berbeda dengan sekolah negeri.
- Sistem rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau ASN lebih banyak mengakomodasi guru di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara guru di bawah Kementerian Agama kerap terabaikan.
Dampaknya:
- Guru yang seharusnya menjadi pilar peradaban malah dipinggirkan.
- Kurangnya motivasi, pengembangan diri, dan stabilitas hidup guru berdampak langsung pada kualitas proses belajar-mengajar.
- Banyak guru potensial akhirnya berpindah profesi karena tidak melihat masa depan di dunia pendidikan Islam.
d. Minimnya integrasi antara tradisi dan modernitas
Alih-alih membangun jembatan antara nilai-nilai Islam dan kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan di banyak negara Islam justru terjebak dalam polarisasi:
- Ada yang terlalu konservatif dan anti-modern.
- Ada juga yang terlalu sekuler dan meninggalkan ruh Islam.
Pendidikan yang ideal adalah yang melahirkan ulama yang juga ilmuwan, dan ilmuwan yang juga beriman. Bukan memilih satu dan membenci yang lain.
4. Trauma Kolonial dan Warisan Ketidakberdayaan yang Tak Disadari
Banyak negara mayoritas Muslim mengalami penjajahan oleh kekuatan Barat selama ratusan tahun. Dari Mesir, Aljazair, dan Suriah di Timur Tengah, hingga Indonesia, India, dan Malaysia di Asia — seluruh jaringan dunia Islam tercerai-berai oleh kolonialisme. Namun, masalah terbesar bukan hanya pada penjajahan fisik, tetapi pada penjajahan mental dan warisan kelembaman sistemik yang terus berlangsung bahkan setelah merdeka.
a. Pendidikan Kolonial: Menciptakan Elite Tapi Memutus Akar
Di Indonesia, sistem pendidikan kolonial Belanda (seperti sekolah ELS, HBS, MULO) dirancang bukan untuk mencerdaskan rakyat secara menyeluruh, melainkan untuk membentuk elite birokrasi lokal yang setia pada penguasa. Pendidikan agama dan pesantren — pusat ilmu Islam lokal — dimarjinalkan dan dianggap terbelakang.
Akibatnya:
- Terjadi keterputusan antara ilmu modern dan tradisi Islam.
- Banyak muslim terpelajar akhirnya mengalami split identity: rasional di satu sisi, namun tidak memiliki pijakan nilai yang utuh.
- Sementara itu, masyarakat awam tetap hidup dalam pola lama, tidak mendapatkan akses ilmu baru, dan bahkan menjadi semakin apatis terhadap perubahan.
Penjajahan tidak hanya mengambil rempah dan emas kita, tapi juga mencetak cara berpikir kita: menjadi pengekor, bukan pencipta.
b. Kehilangan Rasa Percaya Diri Kolektif
Salah satu warisan paling merusak dari kolonialisme adalah inferioritas psikologis kolektif. Umat Islam — yang dahulu menjadi pusat ilmu dunia — mulai percaya bahwa mereka memang tidak mampu lagi bersaing. Muncul mentalitas “yang dari Barat pasti lebih baik” dan “Islam cukup untuk urusan ibadah saja.” Ini diperparah oleh kegagalan elite Muslim pascakolonial untuk membangun sistem pendidikan, ekonomi, dan hukum yang berakar pada nilai-nilai Islam sekaligus modern.
Ahmet T. Kuru menyebutnya sebagai “pasifisme intelektual” — di mana umat Islam lebih nyaman mengingat kejayaan masa lalu daripada bekerja untuk menciptakan kejayaan baru.
“Muslim leaders and societies glorify the past while avoiding innovation and intellectual responsibility in the present.”
— Ahmet T. Kuru, Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment, 2019
c. Kegagalan Melakukan Decolonization of Knowledge
Negara-negara Muslim pascakolonial sering gagal membangun sistem ilmu pengetahuan sendiri. Banyak universitas Islam masih bergantung pada kurikulum buatan luar negeri, minim riset mandiri, dan tidak memiliki strategi nasional dalam membangun keilmuan yang mandiri dan kontekstual.
Contoh nyata:
- Universitas di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir dan Pakistan masih kesulitan masuk daftar 500 universitas terbaik dunia dalam bidang sains dan teknologi.
- Indonesia, dengan jumlah universitas Islam terbanyak, masih memiliki jumlah publikasi ilmiah dan paten sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga non-Muslim seperti Singapura dan Korea Selatan.
- Banyak lulusan kampus Islam tidak dibekali kemampuan berpikir kritis dan wirausaha berbasis ilmu, tapi hanya diarahkan menjadi PNS atau pendakwah pasif.
Penutup: Umat yang Tertinggal Bukan Karena Takdir, Tapi Karena Pilihan
Kemunduran umat Islam dalam peradaban dunia bukanlah takdir, melainkan hasil dari serangkaian keputusan kolektif yang keliru, pembiaran terhadap stagnasi ilmu, dan kegagalan mengenali tantangan zaman secara jujur. Kita tidak kekurangan ajaran—Islam mendorong ilmu, keadilan, dan kepedulian sosial—tetapi kita kekurangan kesadaran, keberanian, dan kemauan untuk menjadikannya nyata.
Dari pencemaran lingkungan oleh tangan-tangan umat sendiri, ketimpangan pendidikan di negeri mayoritas Muslim, hingga mentalitas pascakolonial yang mematikan daya cipta — semua ini menunjukkan bahwa musuh utama kita bukan Barat, bukan orang kafir, bukan teknologi, tapi diri kita sendiri yang kehilangan arah sebagai umat pembawa risalah.
Membangun kembali peradaban Islam bukan soal nostalgia masa lalu, melainkan kerja keras untuk menciptakan masa depan yang layak dihuni anak-anak kita. Kita membutuhkan revolusi pemikiran, reformasi pendidikan, dan kemauan kolektif untuk bertanya: “Apakah kita pantas menyandang gelar khairu ummah jika tak lagi membawa manfaat bagi dunia?”
Referensi dan Literatur yang Digunakan
Buku & Jurnal:
- Ahmet T. Kuru, Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment, Cambridge University Press, 2019.
- Syed Hussein Alatas, The Myth of the Lazy Native, Frank Cass Publishers, 1977.
- Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, Grove Press, 1961.
- Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia, Cambridge University Press, 2005.
- R. William Liddle, Modernizing Indonesia: Political Development and the Role of the Military, in Modern Indonesia: The Post-Colonial State and Economic Development (1996).
- Muqtedar Khan, Islam and Good Governance: A Political Philosophy of Ihsan, Palgrave Macmillan, 2019.
Artikel dan Sumber Online:
- UNESCO, Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education, 2020 – data kesenjangan pendidikan dunia Muslim.
- World Bank Reports – laporan pendidikan dan ketimpangan kualitas guru di negara-negara berkembang.
- Scopus and Nature Index – peringkat dan kontribusi riset negara-negara Muslim.
- Statistik Kemendikbud RI & PISA OECD Reports – laporan ketimpangan mutu pendidikan Indonesia.
Al-Qur’an dan Hadis:
- QS. Ar-Ra’d: 11 – tentang perubahan suatu kaum.
- QS. Al-Mujadilah: 11 – tentang keutamaan orang berilmu.
- Hadis riwayat Bukhari – tentang pentingnya ilmu dan tanggung jawab pemimpin.