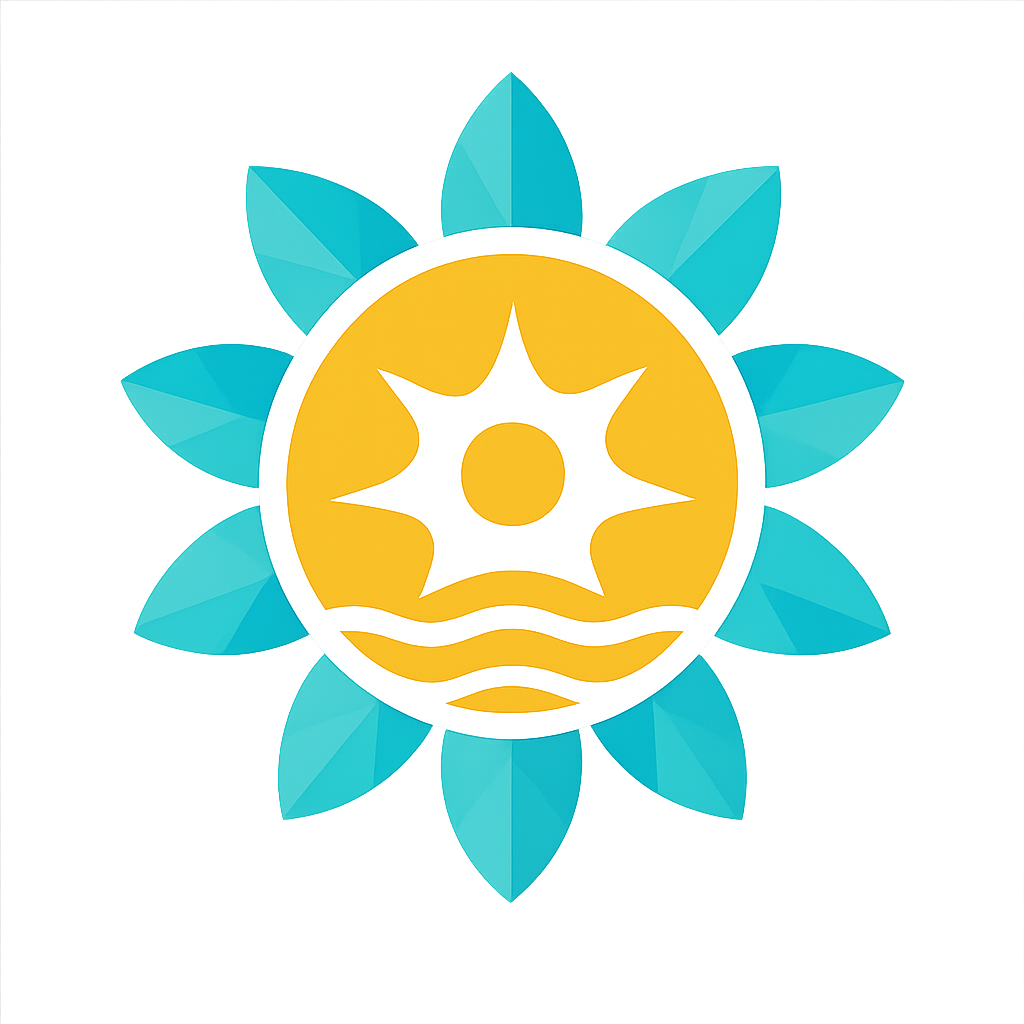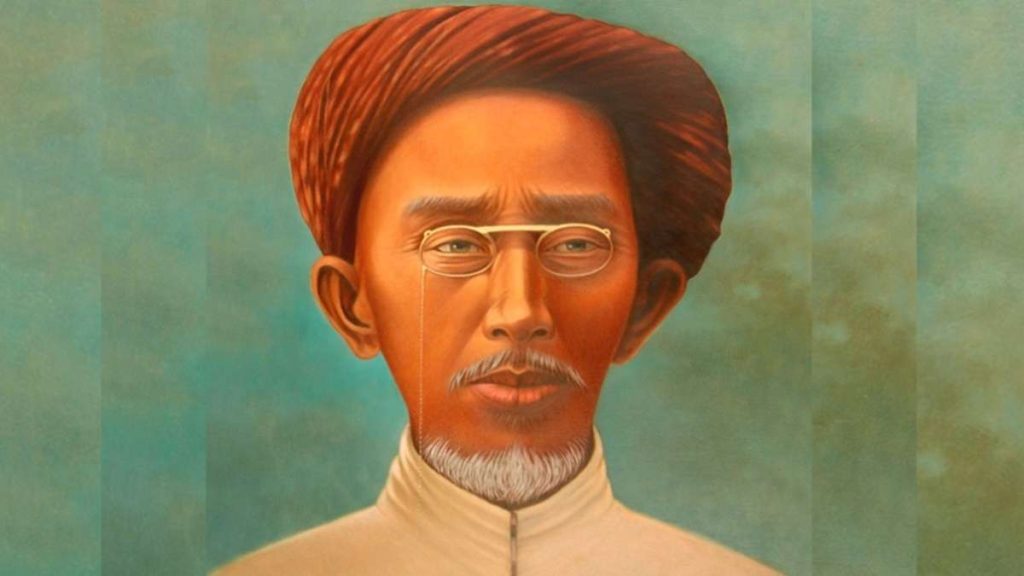Guru sebagai Pahlawan di Tengah Dialektika Kapital
Indonesia, sebuah mozaik bangsa yang dirajut oleh narasi perjuangan dan pengabdian, senantiasa merayakan Hari Pahlawan sebagai momentum refleksi historis. Dalam panggung narasi ini, terselip figur yang akrab namun tak jarang terlupakan, yakni Guru, Sang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Julukan ini, meskipun romantis dan berbau heroik, sejatinya merupakan sebuah konstruksi sosiologis yang menempatkan Guru dalam posisi yang khas: dituntut berkorban tanpa pamrih, namun seringkali minim pengakuan ekonomis dan rentan terhadap badai sosial.
Mengadopsi perspektif sosiologi pendidikan, terutama melalui lensa Pierre Bourdieu, kita dapat memandang profesionalisme dan pengabdian guru sebagai akumulasi Kapital Kultural. Kapital Kultural ini mencakup pengetahuan, kualifikasi formal (sertifikasi), dan yang lebih krusial, habitus atau etos yang terinternalisasi—yaitu semangat pengorbanan yang disetarakan dengan kepahlawanan. Artikel ini bertujuan menelaah secara saintifik-sosiologis bagaimana Kapital Kultural Guru berinteraksi dengan realitas kontemporer, dari krisis etika di sekolah hingga arus digitalisasi, serta bagaimana pandangan keagamaan membentuk etos ini.
Guru dalam Bingkai Romantisme dan Realitas
Konsep Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa adalah puncak dari idealisasi pengabdian. Secara sosiologis, label ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan motivasi sosial. Ia memposisikan guru sebagai figur suci yang tugasnya melampaui perhitungan materi (gaji). Inilah etos pengorbanan yang menjadi Kapital Kultural dalam bentuk habitus ideal bagi profesi ini.
Namun, di balik romantisme tersebut, Guru juga adalah subjek sosial yang beroperasi dalam struktur sekolah dan masyarakat. Keseimbangan antara etos kepahlawanan yang terinternalisasi dan realitas kesejahteraan, otonomi, serta perlindungan hukum menjadi sangat rapuh, menciptakan tegangan yang berkelanjutan dalam medan pendidikan.
Erupsi Krisis Kontemporer: Ketika Kapital Kultural Diuji
Realitas pendidikan masa kini seringkali menampilkan kontradiksi yang mengikis etos kepahlawanan. Berita-berita kekinian menjadi cerminan nyata dari erosi batas-batas profesionalisme dan perlindungan:
1. Konflik Etika dan Otoritas: Kasus Kekerasan Guru
Kasus guru menampar siswa yang berujung mogok massal di sekolah menyoroti kegagalan otoritas dalam mengelola emosi dan menerapkan disiplin berbasis edukasi, bukan kekerasan. Dalam konteks sosiologis, ini adalah pertarungan antara Kapital Simbolik Guru (otoritas yang diakui) melawan Kapital Sosial siswa (dukungan kolektif sesama siswa dan orang tua). Ketika guru menggunakan kekerasan, Kapital Simbolik mereka jatuh, memicu resistensi kolektif yang termanifestasi dalam mogok massal. Aksi mogok tersebut adalah bentuk collective action yang menandakan krisis kepercayaan terhadap institusi sekolah.
2. Diskrepansi Regulasi dan Kebutuhan: Kasus Pungutan Liar (Pungli)
Kasus guru dipecat karena tuduhan pungli—yang diklaim sebagai kesepakatan bersama antara sekolah dan wali murid—menyingkap lubang hitam dalam pendanaan pendidikan. Pungli, di satu sisi, adalah bentuk penyimpangan. Namun, di sisi lain, seringkali ia adalah mekanisme darurat (seperti iuran kesepakatan komite) untuk menutupi defisit anggaran operasional yang tidak memadai. Guru yang dipecat karena terjebak atau mencoba menyelesaikannya adalah korban struktural dari sistem pendanaan yang tidak adil. Etos pengabdian mereka dieksploitasi, dan ketika mencoba mencari solusi finansial, mereka dituduh melanggar hukum, menunjukkan kerentanan status profesional mereka.
3. Kegagalan Sistem dan Dampak Traumatis: Kasus Ledakan Bom Rakitan
Kasus paling tragis, ledakan bom rakitan di masjid sekolah yang diduga dilakukan oleh korban perundungan (balas dendam), adalah kegagalan kolektif sistem pendidikan dalam menciptakan ruang aman. Ledakan ini bukan hanya insiden kriminal, tetapi manifestasi ekstrem dari akumulasi trauma dan alienasi sosial (anomie Durkheimian). Pelaku, yang merasa tidak memiliki Kapital Sosial dan terisolasi, menggunakan kekerasan sebagai satu-satunya bentuk komunikasi yang tersisa. Ini adalah kritik pedas terhadap institusi yang gagal melihat dan mengatasi fenomena perundungan. Guru, yang seharusnya menjadi agen perlindungan dan mediasi, dihadapkan pada dampak kekerasan struktural yang telah mengakar.
Digitalisasi dan Distorsi Kepahlawanan: Perdebatan Kecerdasan Buatan
Arus digitalisasi pendidikan dan adopsi Kecerdasan Buatan (AI) menghadirkan tantangan baru terhadap Kapital Kultural Guru. Perdebatan mengenai pemakaian AI secara sosiologis adalah pertarungan antara Kapital Kultural tradisional (pengetahuan yang melekat pada guru sebagai sumber utama) dan Kapital Kultural teknologis (kemampuan memanfaatkan AI dan teknologi).
Guru masa kini dituntut untuk mentransformasi diri dari Mu’allim (penyampai ilmu) menjadi Murabbi (pendidik jiwa) dan Fasilitator. Jika AI mengambil alih fungsi kognitif rutin (penyampaian materi, koreksi tugas), maka esensi Kepahlawanan Guru harus bergeser:
Guru Pahlawan di era AI adalah mereka yang mampu mengajarkan Humanitas, Etika, dan Kritisitas—hal yang tak dapat disubstitusi oleh algoritma. Mereka menjadi curator pengetahuan dan mentor karakter.
Namun, kesenjangan akses dan literasi digital (Kapital Kultural teknis) antara guru di perkotaan dan pedesaan dapat memperparah ketidaksetaraan pendidikan, menjauhkan guru-guru dari citra “pahlawan” yang up-to-date dan efektif.
Basis Epistemologis: Tinjauan Al-Qur’an dan Hadits
Dalam tradisi Islam, basic etos pengabdian Guru jauh melampaui konsep sekuler tentang profesionalisme. Pendidikan (Tarbiyah, Ta’lim, Ta’dib) adalah amanah ilahiah.
1. Keutamaan Ilmu dan Pendidik: Ayat pertama yang diturunkan, QS. Al-‘Alaq 1-5, menegaskan perintah “Iqra’ (Bacalah)” dan menekankan peran Allah SWT yang mengajar dengan “Qalam” (pena), meletakkan ilmu sebagai poros eksistensi manusia. Guru, sebagai penerus tugas kenabian (warasatul anbiya’), adalah pihak yang meneruskan tradisi membaca dan menulis ini.
2. Etos Pengajaran: Hadits populer menyatakan, “Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya menuju surga.” Ini memberikan dimensi spiritual pada profesionalisme guru; pengabdian bukan sekadar profesi, tetapi jalan ibadah. Hadits lain menekankan pentingnya akhlak (budi pekerti), yang dalam konteks kekinian (kasus perundungan/kekerasan) menjadi penanda bahwa tugas guru bukan hanya mentransfer pengetahuan kognitif, tetapi juga menanamkan moralitas (adab), yang harus dilakukan dengan hikmah (bijaksana), sesuai dengan QS. An-Nahl: 125.
Epilog: Revitalisasi Kapital Kultural Guru dan Peran Kader Bangsa
Kapital Kultural Guru sebagai etos kepahlawanan berada dalam persimpangan jalan. Revitalisasi etos ini tidak dapat lagi hanya bergantung pada romantisme “pahlawan tanpa tanda jasa,” melainkan harus didukung oleh pembentukan Kapital Kultural yang kokoh dan support system yang adil.
Dalam konteks kebangsaan, kontribusi lembaga sosial keagamaan menjadi sangat krusial. Muhammadiyah, misalnya, telah memberikan kontribusi historis yang masif bagi pendidikan kesetaraan di Indonesia dengan mendirikan sekolah modern yang demokratis sejak awal abad ke-20. Muhammadiyah secara konsisten menyediakan Kapital Sosial dan Kapital Kultural institusional yang kuat, memungkinkan akses pendidikan yang luas, dan menekankan ilmu pengetahuan yang rasional dan bermanfaat.
Peran para kader, khususnya guru Muhammadiyah, adalah manifestasi konkret dari idealisme ini. Dalam menjalani tugas-tugasnya, mereka dituntut untuk:
- Menggugah Kesadaran sebagai Pendidik: Menjadi agen perubahan yang berpegang teguh pada prinsip ilmu amaliah dan amal ilmiah. Artinya, mereka harus menjadi profesional yang up-to-date (misalnya, dalam literasi AI), sekaligus menjadi murabbi yang menjunjung tinggi etika Islam progresif (anti-kekerasan, pro-HAM).
- Menjalankan Peran sebagai Warga Negara Aktif: Guru Muhammadiyah didorong untuk tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga terlibat dalam solusi struktural masalah bangsa. Mereka harus berani menyuarakan keadilan dalam isu pungli, menginisiasi program pencegahan bullying, dan memastikan sekolah menjadi ruang yang setara dan demokratis, sesuai dengan semangat reformasi sosial yang diusung oleh organisasi tersebut.
Dengan demikian, kepahlawanan Guru masa kini tidak hanya diukur dari pengorbanan pribadi, tetapi juga dari keberanian mereka untuk menuntut dan membangun sistem yang adil (regulasi, kesejahteraan, perlindungan) serta kesuksesan mereka dalam menanamkan habitus rasionalitas dan moralitas pada siswa. Pahlawan masa kini adalah yang mampu mengintegrasikan etos spiritual dengan tuntutan profesional, sekaligus aktif sebagai warga negara yang kritis dan konstruktif. Sebagai guru (dan warga) Muhammadiyah, sudahkah kita merenungi hal di atas?
Bojonegoro, 10 November 2025
Oleh: Ajun Pujang Anom (Penulis adalah Anggota Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Bojonegoro)